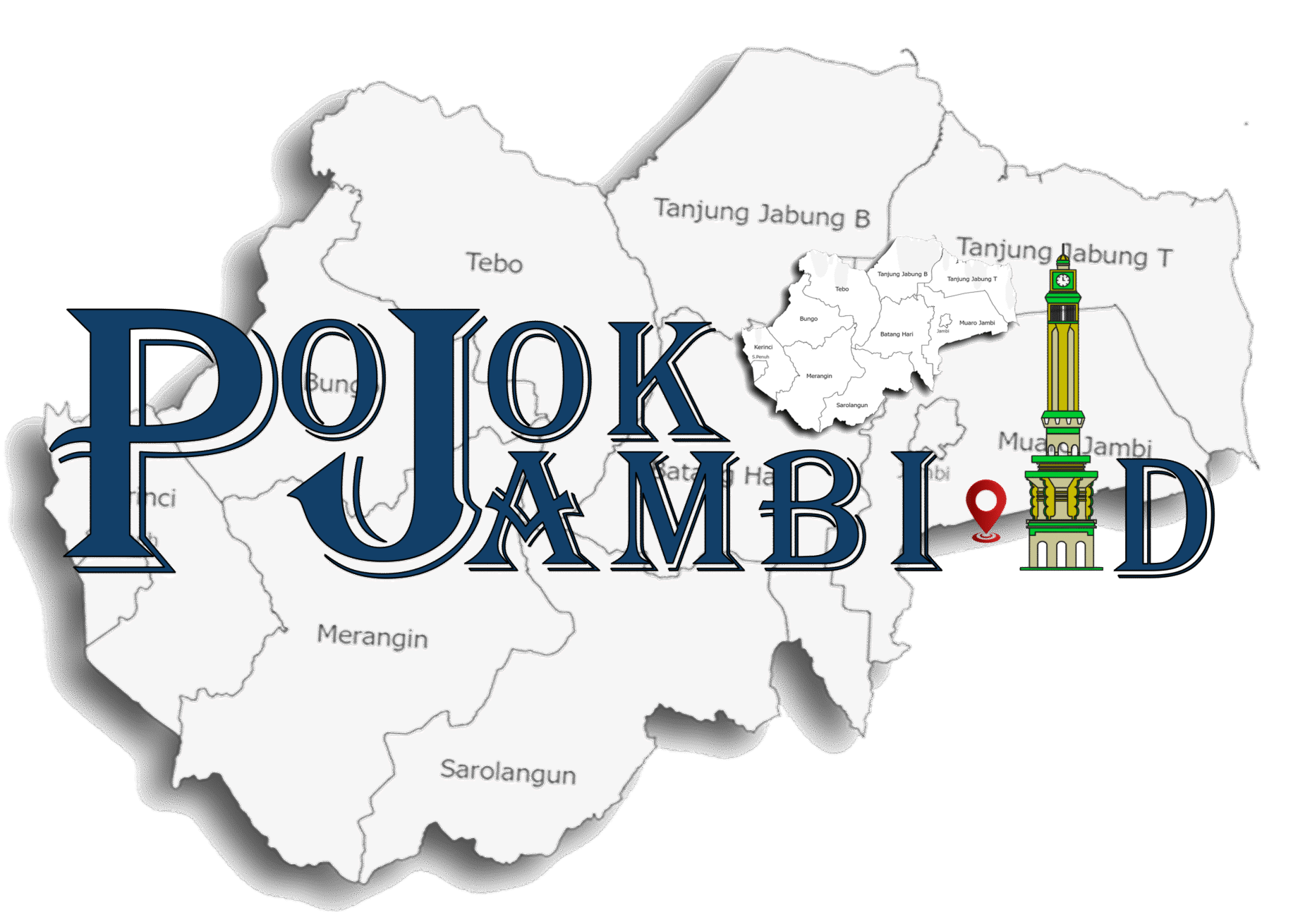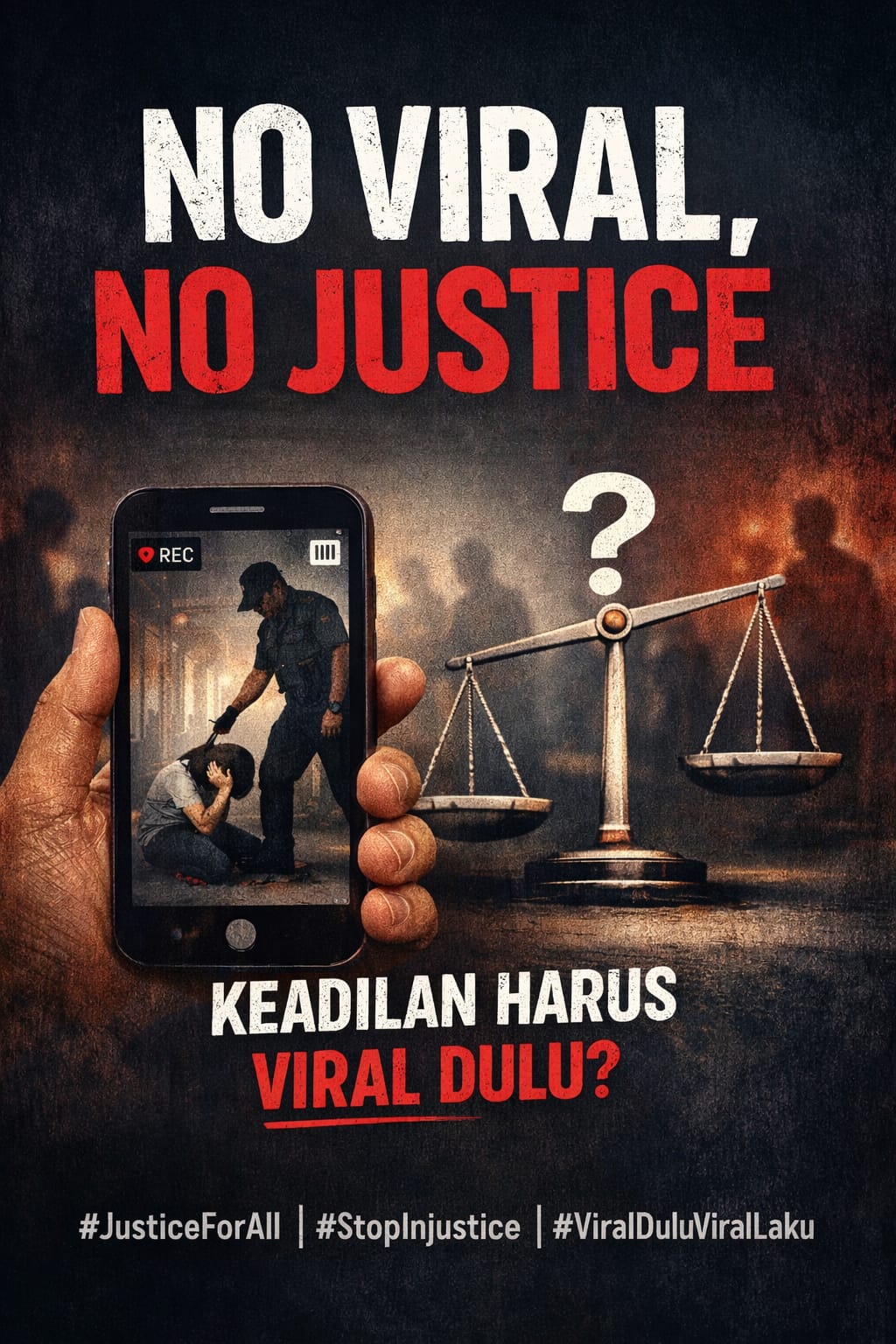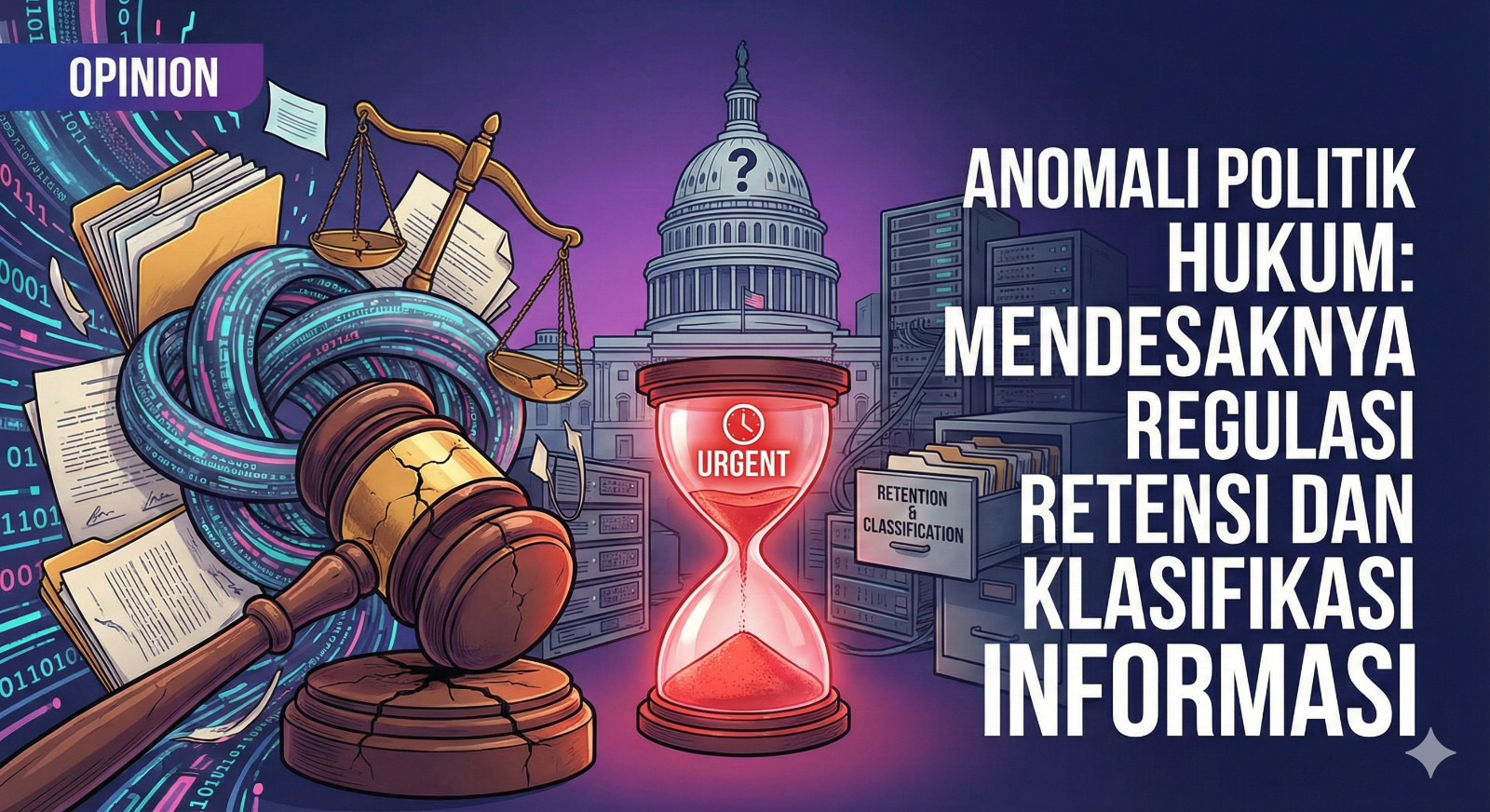Menakar Kembali “Hak Raja” : Urgensi standarisasi pemberian Grasi, Amnesti, abolis dan Rehabilitasi
Penulis : Slamet Putra Dwi Arianto (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi)

Oleh : Slamet Putra Dwi Arianto (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi)
Pojokjambi.id – Dalam sistem ketatanegaraan modern, prinsip kekuasaan pada hakikatnya tidak diterapkan secara absolut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyediakan mekanisme korektif berupa kewenangan prerogratif Presiden di bidang Yudisial, yaitu pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 UUD 1945.
Dari perspektif politik huku, kewenangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan Presiden di atas supremasi hukum, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki keterbatasan dan kekuatan hukum formal yang berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Oleh karen itu, hak prerogratif tersebut berfungsi sebagai instrument checks anda balances terakhir Ketika mekanisme peradilan formal tidak mampu sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan.
Meskipun demikian, kewenangan dikresioner tersebut senantiasa berada dalam ketegangan konseptual dengan prinsip negara hukum. Konsep negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keterukuran, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Sebaliknya, pemberian grasi dan amnesti secara historis berakar pada konsep “hak raja” yang bersifat absolut dan sangat bergantung pada pertimbangan subjektif penguasa. Persoalan muncul Ketika diskresi presiden dalam sistem demokrasi dijalankan tanpa Batasan parameter yang jelas dan terukur, sehingga membuka peluang terjadinya pergeseran fungsi kewenangan tersebut dari instrument keadilan menjadi alat atau komoditas kepentingan politik.
Pada kondisi saat ini, politik hukum yang mengatur implementasi pasal 14 UUD 1945 masih menyisakan celah pengaturan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU Grasi, cenderung lebih menekankan pengatura pada aspek procedural dan administrative, sementara dimensi materiil-substantif belum diatur secara memadai. Akibatnya, meskipun mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan telah diatur secara jelas, belum terdapat rumusan kriteria hukum yang baku dan terukur mengenai dasar pertimbangan yang menentukan kelayakan seoran terpidana untuk memperoleh pengampunan atau rehabilitasi nama baik.
Tidak adanya standar persyaratan materiil yang jelas tersebut menciptakan area abu-abu dalam praktik pelaksanaannya. Secara logis, keetika hukum gagal menetapkan Batasan yang tegas, ruang kekosongan tersebut berpotensi diisi oleh faktor-faktor di luar pertimbangan hukum. Faktor-faktor tersebut dapat berupa lobi politik, relasi personal, maupun tekanan dari opini public. Konsekuensinya, pemberian grasi atau amnesti menjadi rentan dipersepsikan bukan sebagai wujud pertimbangan kemanusiaan atau koreksi atas kekeliruan peradilan, melainkan sebagai bagian dari praktik tawa-menawar politik.
Khusus dalam hal Grasi, absennya standarisasi syarat berpotensi merendahkan martabat peradilan. Bayangkan, sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang diputuskan melalui proses pembuktian panjang oleh hakim, bisa dianulir begitu saja oleh Keputusan Presiden. Tanpa standar yang jelas—misalnya syarat adanya novum (bukti baru) non-yudisial atau kondisi kemanusiaan ekstrem yang terverifikasi medis—grasi bisa menjadi bentuk intervensi eksekutif yang mencederai independensi yudikatif.
Memang, konstitusi mewajibkan Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) untuk Grasi dan Rehabilitasi. Namun, dalam politik hukum ketatanegaraan kita, “memperhatikan” tidak bermakna “mematuhi”. Pertimbangan MA seringkali bersifat rahasia dan tidak mengikat. Tanpa standarisasi yang memaksa transparansi alasan penerimaan atau penolakan pertimbangan MA, mekanisme ini hanyalah formalitas birokrasi tanpa bobot check and balances yang nyata.
Beralih ke Amnesti dan Abolisi, kerawanan politisnya jauh lebih tinggi. Instrumen ini biasanya digunakan untuk tindak pidana yang terkait politik. Namun, tanpa definisi yang tegas dalam undang-undang mengenai apa itu “kepentingan negara” yang membenarkan amnesti, presiden bisa terjebak memberikan pengampunan kepada kelompok yang sebenarnya mengancam kedaulatan, atau sebaliknya, menolak memberikan amnesti kepada aktivis hak asasi manusia karena perbedaan preferensi politik.
Kewajiban meminta pertimbangan DPR dalam pemberian Amnesti dan Abolisi juga menghadapi tantangan serupa. DPR adalah lembaga politik. Tanpa panduan standar hukum yang objektif, pertimbangan DPR akan murni berbasis kalkulasi dukungan politik di parlemen. Akibatnya, nasib hukum seseorang atau sekelompok orang tidak ditentukan oleh derajat kesalahannya atau kemanfaatan hukumnya, melainkan oleh konstelasi koalisi partai politik saat itu.
Sementara itu, Rehabilitasi seringkali menjadi anak tiri dalam diskursus ini. Padahal, rehabilitasi adalah hak fundamental bagi mereka yang menjadi korban peradilan sesat (miscarriage of justice). Ketiadaan standar baku tentang bagaimana mekanisme pemulihan hak dilakukan secara otomatis pasca-putusan peninjauan kembali, membuat rehabilitasi sering kali hanya indah di atas kertas namun sulit direalisasikan karena birokrasi yang berbelit tanpa SOP yang jelas.
Kekosongan parameter yang terukur ini melahirkan diskriminasi. Mengapa koruptor A dengan alasan sakit bisa mendapat grasi, sementara narapidana B dengan penyakit yang sama tetap mendekam di sel? Tanpa standarisasi syarat yang objektif (misalnya standar medis independen yang baku), disparitas keputusan ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap integritas istana sebagai benteng terakhir keadilan.
Jika kita melihat tren global, negara-negara hukum modern mulai bergerak membatasi hak pengampunan eksekutif. Mereka menerapkan Clemency Guidelines yang ketat, yang mencakup syarat perilaku selama masa tahanan, tingkat penerimaan kesalahan (remorse), hingga dampak terhadap korban. Politik hukum Indonesia tertinggal karena masih memosisikan hak ini sebagai kewenangan absolut yang “sakral” dan minim parameter akuntabilitas.
Oleh karena itu, arah politik hukum nasional harus segera dikoreksi. Kita membutuhkan regulasi—baik revisi UU atau aturan turunan—yang menetapkan matriks penilaian (scoring) objektif. Syarat pemberian tidak boleh lagi hanya kalimat normatif, tetapi harus dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif. Transparansi proses menjadi kunci; publik berhak tahu alasan di balik setiap tanda tangan Presiden dalam dokumen pengampunan.
Standarisasi ini sesungguhnya bukan untuk mengekang Presiden, melainkan justru untuk melindungi wibawa lembaga kepresidenan. Dengan adanya standar yang jelas, Presiden terlindungi dari tuduhan intervensi kasus atau jual-beli hukum. Keputusan Presiden akan memiliki legitimasi moral dan hukum yang kuat karena didasarkan pada indikator yang dapat diuji, bukan sekadar intuisi atau bisikan lingkaran kekuasaan.
Ke depan, pembentuk undang-undang perlu merumuskan naskah akademik yang komprehensif untuk menyatukan rezim pengampunan ini dalam satu atap regulasi yang lebih modern. Perlu ada pelibatan tim ahli independen (selain MA dan DPR) dalam memverifikasi syarat-syarat tersebut sebelum sampai ke meja Presiden, guna memastikan objektivitas data.Sebagai konklusi, Grasi, Rehabilitasi, dan Amnesti adalah instrumen mulia untuk menghadirkan keadilan restoratif dan kemanusiaan.
Namun, tanpa standarisasi syarat yang ketat, instrumen mulia ini bisa merosot menjadi alat impunitas. Negara hukum menuntut agar setiap tetes tinta kekuasaan yang tumpah di atas lembar keputusan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan konstitusional. Standarisasi adalah jalan mutlak untuk memastikan hal tersebut.