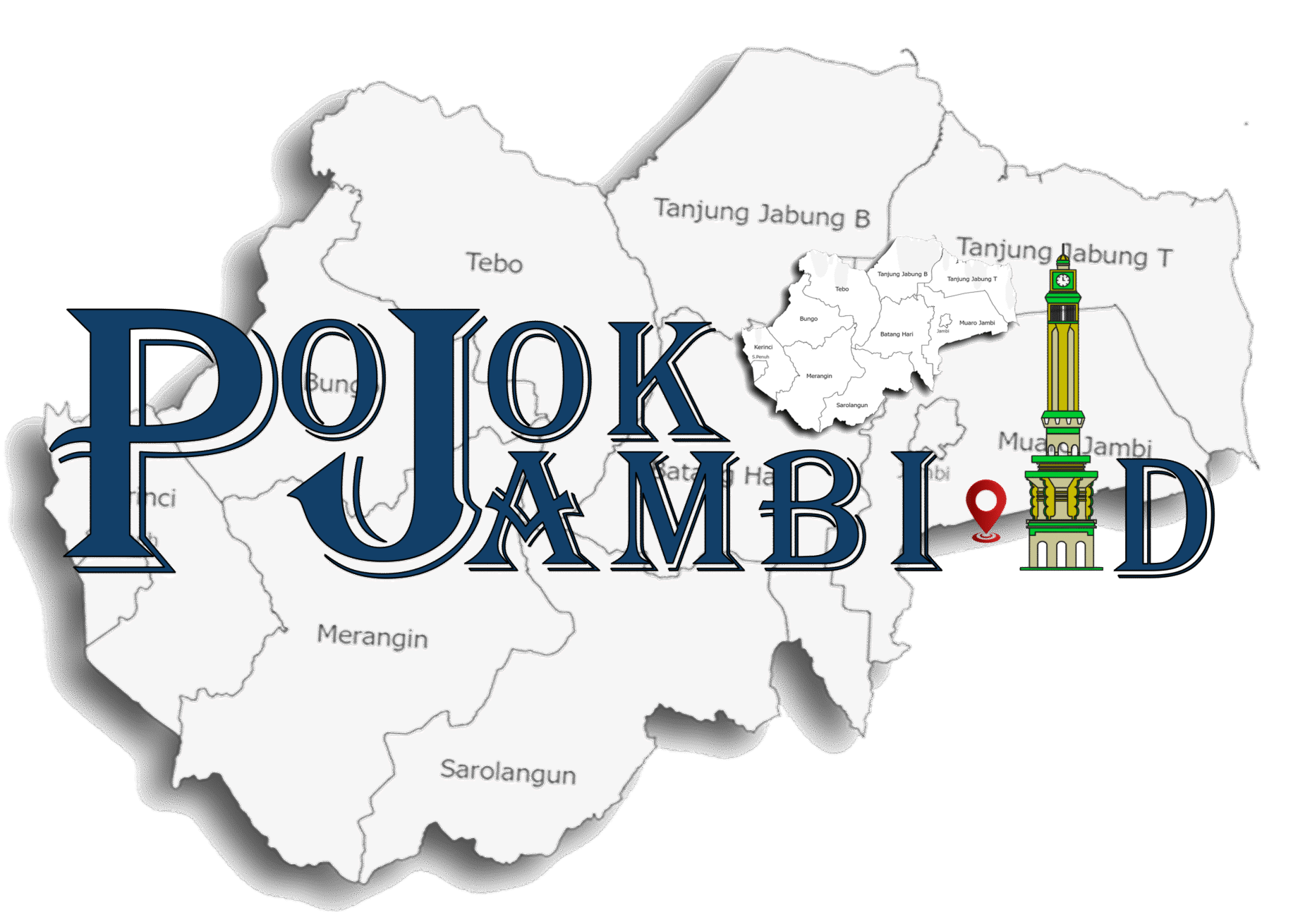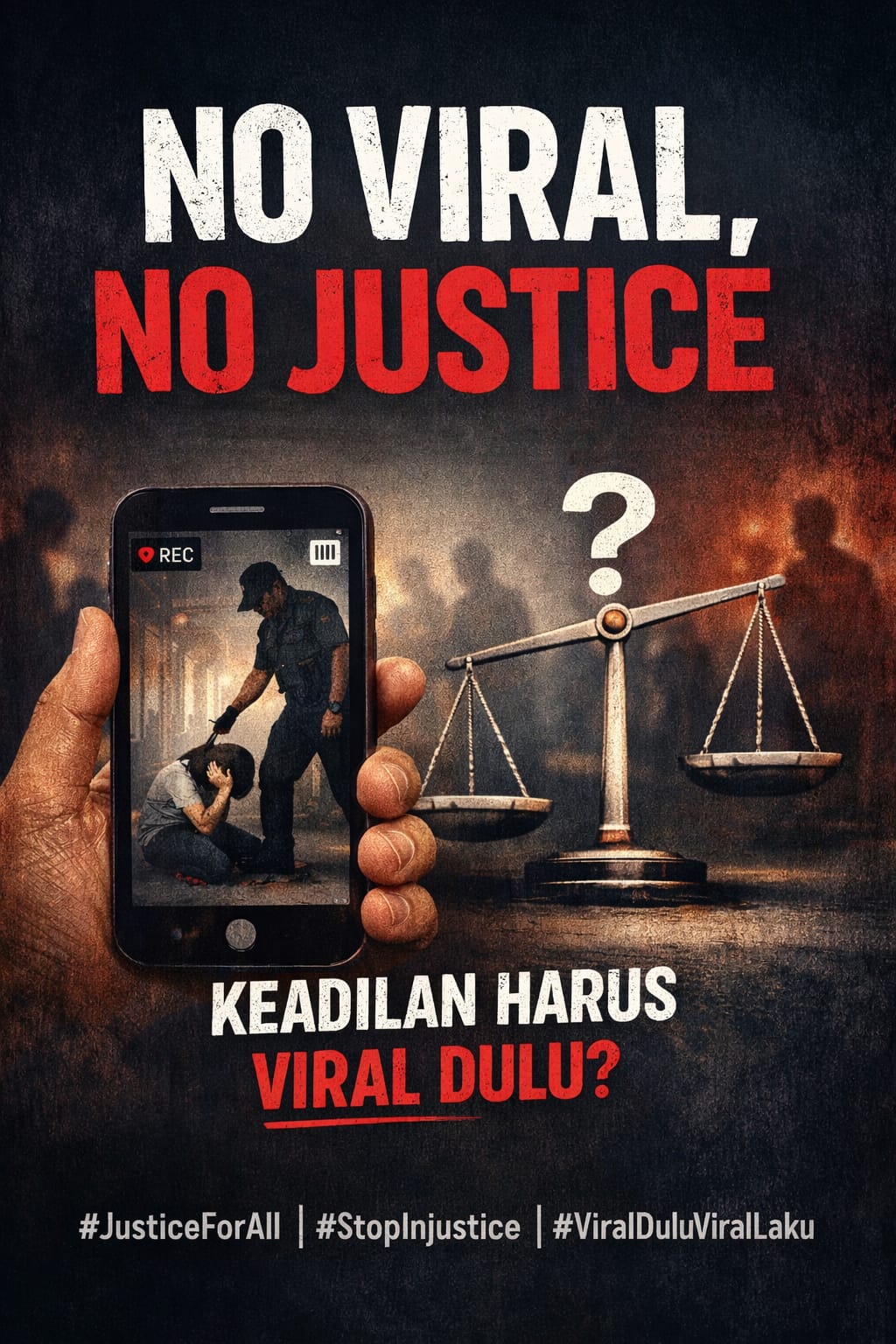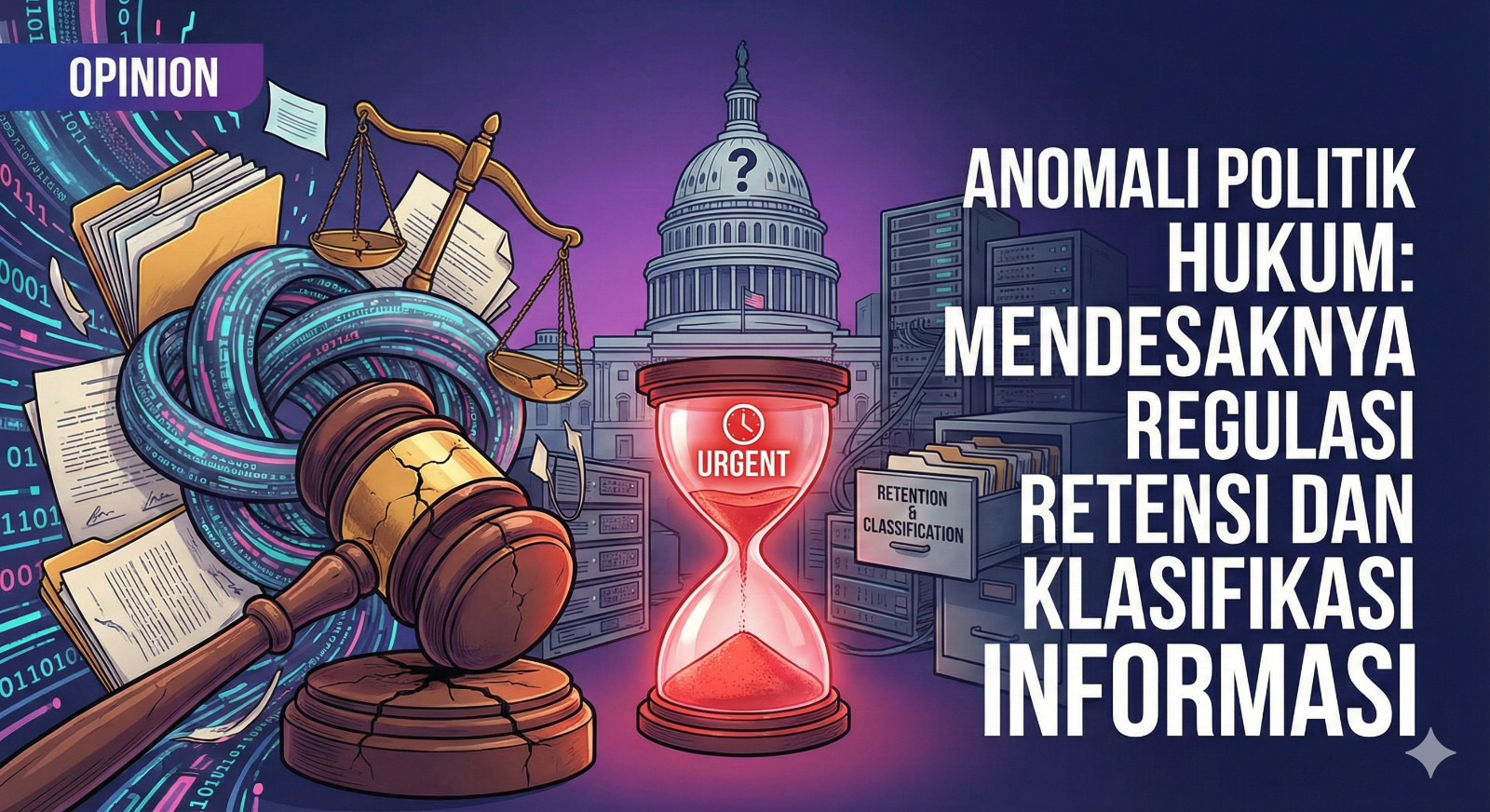Gerakan Membeli Tanah Hutan adalah bentuk pelemahan dan ketidak percayaan kepada Negara untuk mengelola, merawat dan melindungi Hutan di Indonesia
Penulis : Agus Salim (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi)

Oleh : Agus Salim (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi)
Pojokjambi.id – Indonesia adalah suatu negara dengan iklim tropis yang terdiri atas ribuan pulau. Daratan Indonesia memang tidak seluas lautannya, tetapi hutan di Indonesia sangat banyak, mulai dari ujung Aceh (sabang) hingga Merauke (Papua). Beberapa Pekan terakhir ini, banjir terjadi di Indonesia khususnya beberapa daerah dipulau Sumatera. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan Faktor Perbuatan manusia.
Faktor alam memang tidak dapat disalahkan, tetapi faktor buatan yang perlu dievaluasi. Manusia saat ini telah kehilangan kesadarannya hingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan banyak pihak, termasuk hutan sebagai lingkungan hidup. Hutan adalah habitat dari ribuan spesies makhluk hidup yang saling bergantung.
Aksi manusia menebangi hutan untuk memenuhi maksud dari dalam dirinya sendiri memang perlu diadili. Alasan mereka melakukan penebangan hutan beragam, mulai dari ingin membuka lahan tanam baru hingga untuk kebutuhan komersil lainnya. Namun, hal yang patut disayangkan karena mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat deforestasi yang dilakukan, banyak aneka flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut terancam keberadaannya, dan bahkan dapat menyebabkan bencana banjir seperti yang terjadi di beberapa tempat dipulau Sumatra akibat dari deforestasi yang dilakukan.
Fenomena membeli tanah untuk dijadikan hutan akhir-akhir ini semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan dan perubahan iklim. Praktik ini umumnya dilakukan oleh individu, komunitas, maupun korporasi dengan tujuan konservasi, restorasi ekosistem, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Pada satu sisi, langkah ini mencerminkan tanggung jawab ekologis yang patut diapresiasi, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum agraria dan tata kelola pertanahan yang tidak sederhana.
Secara ekologis, pembelian tanah untuk dijadikan hutan berkontribusi positif terhadap pemulihan fungsi lingkungan. Hutan berperan penting sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, serta penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi laju deforestasi dan degradasi lahan yang tinggi, inisiatif ini dapat menjadi solusi alternatif di luar kebijakan negara yang kerap terkendala birokrasi dan konflik kepentingan.
Namun demikian, dari perspektif hukum agraria, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai fungsi sosial hak atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial, artinya pemanfaatan tanah tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan pemilik, melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Menjadikan tanah sebagai hutan konservasi pada prinsipnya sejalan dengan fungsi sosial tersebut, sepanjang tidak menutup akses masyarakat adat atau lokal yang telah lama bergantung pada tanah tersebut.
Permasalahan muncul ketika praktik ini dilakukan tanpa memperhatikan status hukum tanah dan kawasan. Tidak semua tanah dapat secara bebas dialihfungsikan menjadi hutan, khususnya jika berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara, tanah ulayat masyarakat adat, atau wilayah dengan peruntukan tertentu dalam rencana tata ruang. Pembelian tanah untuk hutan yang mengabaikan aspek ini justru berpotensi menimbulkan konflik agraria baru, yang ironisnya bertentangan dengan tujuan pelestarian itu sendiri.
Selain itu, terdapat risiko komersialisasi konservasi, di mana pembelian tanah atas nama “hutan” digunakan sebagai legitimasi penguasaan lahan skala besar. Praktik semacam ini dapat menjelma menjadi bentuk baru penguasaan tanah yang eksklusif, menyingkirkan masyarakat lokal atas nama pelestarian lingkungan. Jika tidak diatur dengan jelas, konservasi dapat berubah menjadi instrumen penguasaan tanah yang tidak adil.
Oleh karena itu, fenomena membeli tanah untuk dijadikan hutan perlu direspons dengan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan. Negara harus hadir melalui pengaturan yang memastikan bahwa inisiatif konservasi berbasis kepemilikan tanah tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan masyarakat adat, dan kepastian hukum pertanahan. Skema seperti perhutanan sosial, kemitraan konservasi, atau pengakuan hutan adat dapat menjadi alternatif yang lebih inklusif dibandingkan penguasaan tanah secara individual atau korporatif.
Membeli tanah untuk dijadikan hutan bukanlah persoalan hitam putih. Ia adalah fenomena yang lahir dari niat baik, namun membutuhkan kehati-hatian hukum dan sosial. Tanpa pengaturan dan pengawasan yang tepat, niat menyelamatkan lingkungan dapat berubah menjadi sumber konflik agraria baru. Sebaliknya, dengan tata kelola yang benar, fenomena ini dapat menjadi bagian dari solusi berkelanjutan bagi krisis lingkungan dan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
Membeli tanah untuk dijadikan hutan merupakan gejala sosial–hukum yang tidak dapat dipahami secara normatif semata. Praktik ini berada pada persimpangan antara kehendak politik negara, dinamika kekuasaan, serta realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini menuntut pendekatan interdisipliner, khususnya melalui perspektif politik hukum dan sosiologi hukum.
Dalam kerangka politik hukum, hukum dipahami sebagai produk kebijakan negara yang mencerminkan pilihan ideologis dan konfigurasi kekuasaan. Politik hukum agraria dan kehutanan Indonesia secara normatif bertumpu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA, yang menegaskan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, lemahnya implementasi kebijakan konservasi dan tingginya konflik agraria mendorong munculnya aktor non-negara yang mengambil peran negara melalui pembelian tanah untuk tujuan pelestarian hutan.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum sebagai kebijakan negara dan hukum sebagai respons sosial. Dari sudut pandang politik hukum, pembelian tanah untuk hutan oleh aktor privat dapat dipandang sebagai koreksi sosial terhadap kegagalan negara, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan legitimasi. Negara tetap memegang mandat konstitusional atas pengelolaan sumber daya alam, sehingga ketika fungsi tersebut dijalankan oleh aktor privat, terjadi pergeseran locus kekuasaan yang berpotensi melemahkan otoritas hukum publik.
Sementara itu, sosiologi hukum memandang hukum sebagai institusi sosial yang hidup (living law), dipengaruhi oleh nilai, struktur sosial, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, membeli tanah untuk dijadikan hutan tidak sekadar perbuatan hukum perdata, melainkan tindakan sosial yang membentuk pola relasi baru antara pemilik tanah, masyarakat lokal, dan negara. Di banyak kasus, praktik ini diterima secara sosial karena dipersepsikan sebagai solusi atas kerusakan lingkungan, meskipun secara hukum belum tentu sepenuhnya sejalan dengan tata ruang atau hak-hak komunal masyarakat.
Sosiologi hukum juga mengungkap adanya potensi ketimpangan sosial dalam praktik konservasi berbasis kepemilikan tanah. Aktor dengan modal ekonomi dan akses hukum yang kuat cenderung lebih mampu melegitimasi penguasaan tanah atas nama lingkungan. Sebaliknya, masyarakat adat dan petani kecil sering kali berada pada posisi subordinat, di mana praktik konservasi justru membatasi akses mereka terhadap tanah yang secara sosial dan historis telah mereka kelola. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan sosial, melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial yang menguntungkan kelompok tertentu.
Kombinasi politik hukum dan sosiologi hukum memperlihatkan bahwa masalah utama bukan pada tujuan konservasi, melainkan pada desain hukum dan relasi kekuasaan yang melingkupinya. Ketika hukum hanya menekankan aspek formal kepemilikan tanpa mempertimbangkan realitas sosial, maka terjadi kesenjangan antara law in the books dan law in action. Kesenjangan inilah yang kerap menjadi sumber konflik agraria dan delegitimasi hukum di mata masyarakat.
Oleh karena itu, negara perlu merumuskan politik hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial. Pendekatan sosiologis harus diintegrasikan ke dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pertanahan dan kehutanan. Skema seperti pengakuan hutan adat, perhutanan sosial, serta kemitraan konservasi berbasis komunitas merupakan contoh kebijakan yang menggabungkan legitimasi politik hukum dengan penerimaan sosial (social acceptance).
Dengan demikian, fenomena membeli tanah untuk dijadikan hutan mencerminkan ujian bagi hukum di Indonesia: apakah hukum mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan pelestarian lingkungan secara bersamaan, atau justru menjadi alat legitimasi kekuasaan baru. Dalam perspektif politik hukum dan sosiologi hukum, keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi tertulis, tetapi oleh sejauh mana hukum mampu hidup, diterima, dan dirasakan adil oleh masyarakat.