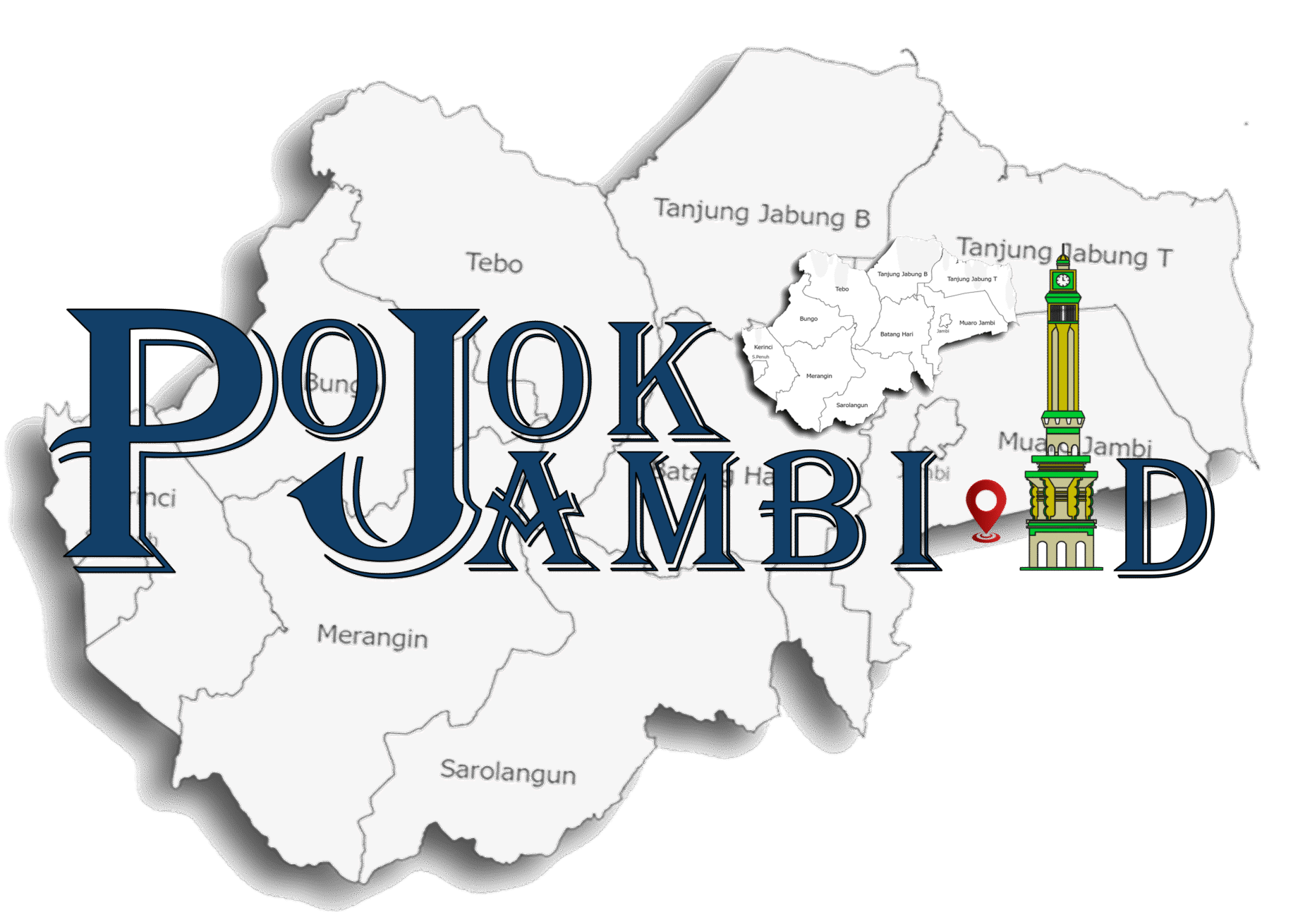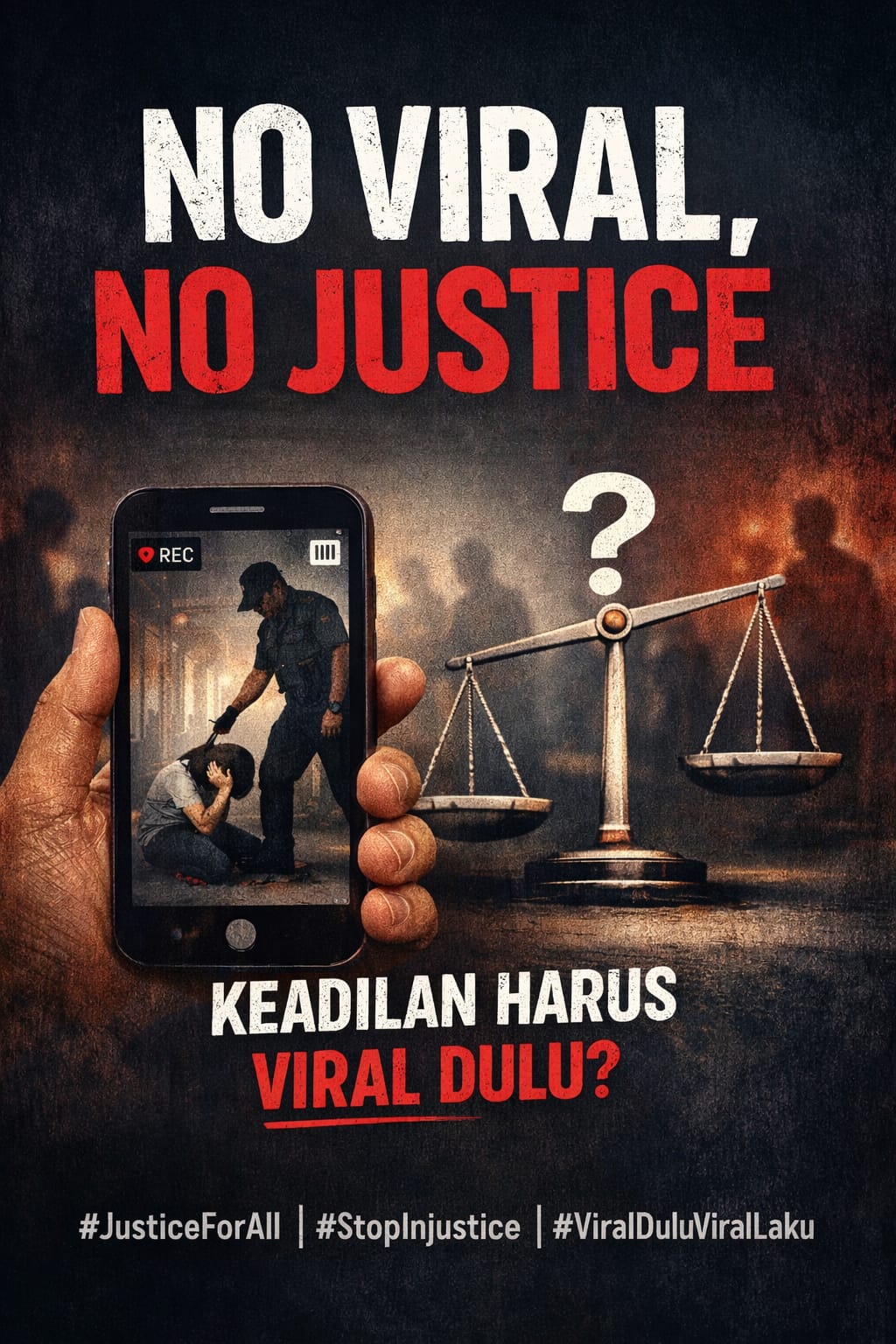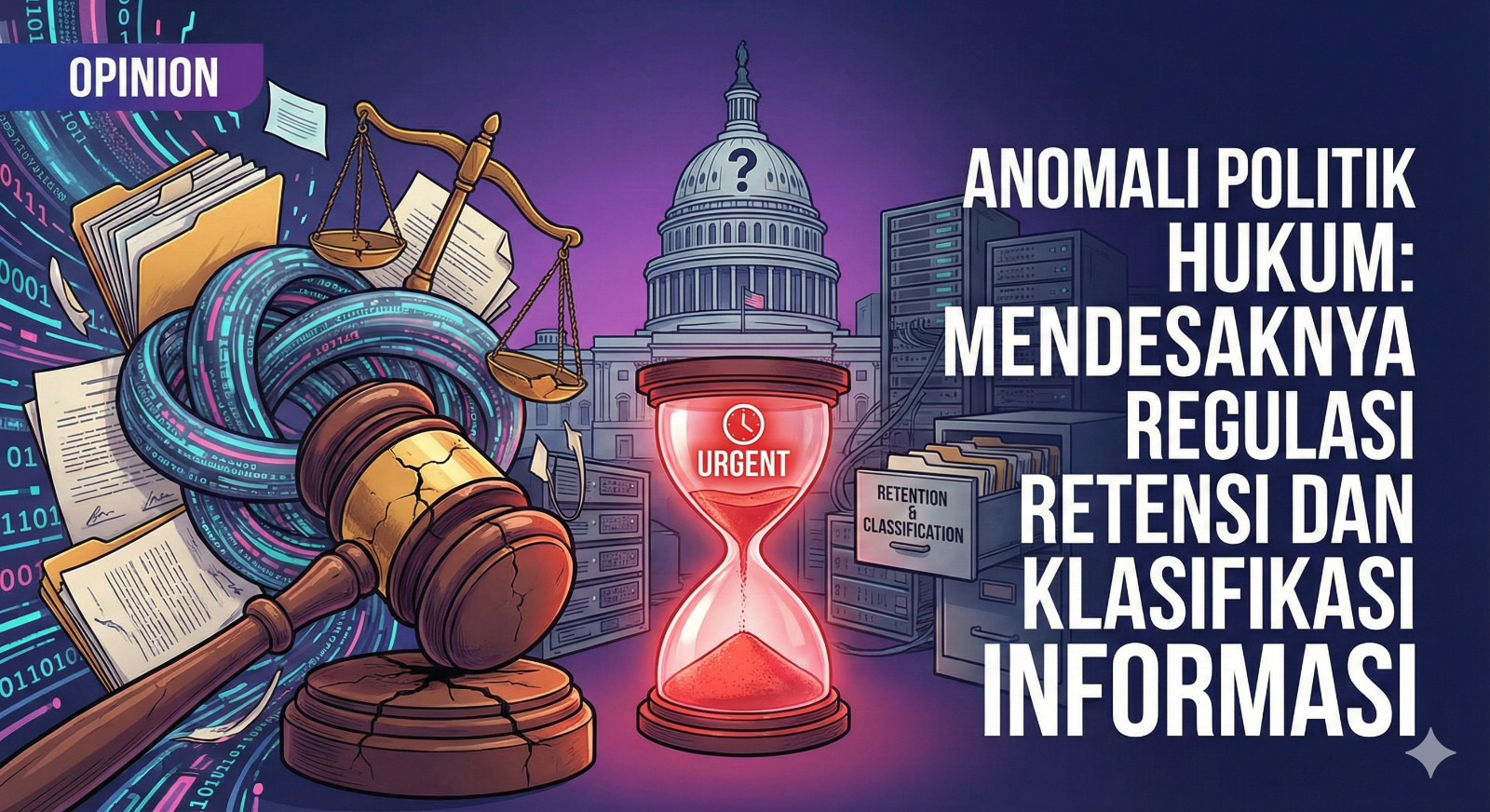Benturan Globalisasi dan Kekosongan Hukum: Lonceng Kematian bagi Masyarakat Adat?
Penulis : Yudha Eko Prastito (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi)

Oleh : Yudha Eko Prastito (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi)
Pojokjambi.id – Dalam kacamata sosiologi hukum, fungsi utama hukum bukan sekadar seperangkat aturan kaku, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) dan benteng pertahanan masyarakat terhadap perubahan yang destruktif. Di abad ke-21, tantangan terbesar bagi benteng ini adalah arus globalisasi ekonomi yang massif.
Globalisasi membawa logika pasar bebas yang menuntut efisiensi, standarisasi, dan kepastian modal yang sering kali tidak mengenal batas-batas yurisdiksi tradisional.Tekanan global ini bermanifestasi dalam bentuk ekspansi korporasi multinasional yang lapar akan sumber daya alam. Demi memenuhi rantai pasok global (global supply chain), mulai dari minyak sawit hingga nikel untuk baterai kendaraan listrik, investor membutuhkan akses terhadap lahan yang luas. Dalam logika bisnis internasional, kepastian hukum atas tanah adalah syarat mutlak. Mereka menuntut lahan yang clean and clear secara formal untuk menjamin keamanan investasi mereka.
Di sinilah letak kerawanan fundamental bagi Indonesia. Ketika tekanan eksternal begitu kuat, sistem hukum internal kita justru menyisakan lubang besar: ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (UU MHA). Meskipun Pasal 18B UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat, pengakuan ini bersifat deklaratif namun lemah dalam eksekusi tanpa aturan turunan yang bersifat operasional dan komprehensif.
Secara deduktif, kita melihat benturan dua rezim hukum. Di satu sisi ada hukum negara yang positivistik dan birokratis—yang menjadi bahasa pengantar globalisasi. Di sisi lain, ada hukum yang hidup (the living law) milik masyarakat adat yang bersifat komunal, magis-religius, dan tidak tertulis. Tanpa UU MHA sebagai jembatan atau penerjemah antara kedua entitas ini, masyarakat adat dipaksa bertarung di arena yang tidak seimbang.
Akibat langsung dari kekosongan hukum ini adalah kerawanan status kepemilikan wilayah adat. Dalam perspektif hukum formal saat ini, wilayah adat yang tidak teradministrasi sering kali diklaim sepihak sebagai tanah negara atau wilayah konsesi. Ini membuka celah lebar bagi praktik perampasan lahan (land grabbing). Hutan dan tanah yang telah dikelola ratusan tahun bisa tiba-tiba beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur hanya karena selembar izin konsesi yang diterbitkan di Jakarta, tanpa sepengetahuan masyarakat lokal.
Kondisi ini memicu konflik agraria yang bersifat struktural dan berkepanjangan. Data dari berbagai lembaga bantuan hukum dan LSM lingkungan menunjukkan tren peningkatan konflik antara masyarakat adat dengan korporasi. Tanpa UU MHA, penyelesaian konflik menjadi bias karena negara cenderung menggunakan kacamata hukum positif yang mengagungkan bukti tertulis (sertifikat), sesuatu yang jarang dimiliki oleh masyarakat adat.
Kerawanan selanjutnya yang tak kalah mengerikan adalah kriminalisasi. Absennya perlindungan hukum membuat aktivitas tradisional masyarakat adat sering kali dianggap ilegal. Petani yang berladang di wilayah leluhurnya bisa didakwa merambah hutan negara. Tetua adat yang mempertahankan tanah ulayat bisa dijerat dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pendudukan lahan tanpa izin. Hukum pidana dijadikan senjata untuk membungkam resistensi terhadap ekspansi modal.
Globalisasi menjanjikan kesejahteraan, namun tanpa proteksi UU MHA, masyarakat adat justru mengalami marginalisasi ekonomi. Ketika sumber daya alam mereka dieksploitasi, mereka tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) untuk mendapatkan bagi hasil yang adil. Mereka tersingkir dari tanah yang menjadi alat produksi utama mereka, dan sering kali berakhir menjadi buruh kasar di tanah leluhur mereka sendiri.
Dari sudut pandang ekologi manusia, masyarakat adat adalah penjaga alam terbaik. Kearifan lokal mereka terbukti ampuh menjaga keseimbangan ekosistem. Kekosongan hukum yang mempermudah konversi hutan adat menjadi lahan industri berdampak fatal pada lingkungan. Hilangnya hak kelola masyarakat adat berkorelasi lurus dengan deforestasi dan degradasi lingkungan, yang pada akhirnya memperparah krisis iklim global.
Ancaman yang lebih halus namun mematikan adalah epistemisida atau pembunuhan sistem pengetahuan. Basis budaya masyarakat adat melekat erat pada wilayahnya. Ketika wilayah itu hilang diambil alih kekuatan modal, maka ritual, bahasa, dan pengetahuan pengobatan tradisional yang melekat pada tanah tersebut juga ikut punah. Kita tidak hanya kehilangan manusia, tapi juga perpustakaan pengetahuan peradaban nusantara.
Masuknya kepentingan global tanpa filter hukum yang kuat juga memicu perpecahan internal (disintegrasi sosial). Sering kali terjadi kooptasi terhadap elit-elit adat oleh pihak eksternal untuk memuluskan perizinan, yang kemudian memicu konflik horizontal antar sesama anggota masyarakat adat. Solidaritas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat paguyuban (gemeeinschat) hancur berkeping-keping oleh intrusi kepentingan materialistis.
Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa peraturan sektoral (seperti di bidang kehutanan atau agraria) sudah cukup. Namun, fakta sosiologis membuktikan sebaliknya. Peraturan sektoral sering kali tumpang tindih dan memiliki ego sektoral masing-masing. Hanya UU MHA yang bersifat lex specialis dan komprehensif yang mampu menyatukan serpihan perlindungan hukum tersebut menjadi sebuah tameng yang utuh.
Dunia internasional sebenarnya mulai bergerak ke arah pengakuan hak asasi (seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat/UNDRIP). Namun, tanpa ratifikasi dalam hukum positif nasional, instrumen internasional tersebut hanyalah macan kertas. Indonesia berisiko dikucilkan dalam pergaulan global yang semakin sadar HAM jika terus membiarkan masyarakat adatnya tergerus tanpa perlindungan.
Maka, kesimpulannya sangat jelas. Membiarkan RUU MHA terkatung-katung adalah bentuk pembiaran negara (state negligence) terhadap warga negaranya yang paling rentan. Negara gagal menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Setiap detik penundaan pengesahan UU ini dibayar mahal dengan hilangnya tanah, kebebasan, dan identitas masyarakat adat.
Sebagai negara hukum, kita tidak boleh membiarkan hukum rimba (di mana yang kuat secara modal memangsa yang lemah) berlaku di negeri ini. Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan pertaruhan terakhir untuk menyelamatkan warisan kemanusiaan kita dari gilas roda globalisasi yang tak kenal ampun. Saatnya negara hadir, sebelum semuanya terlambat.