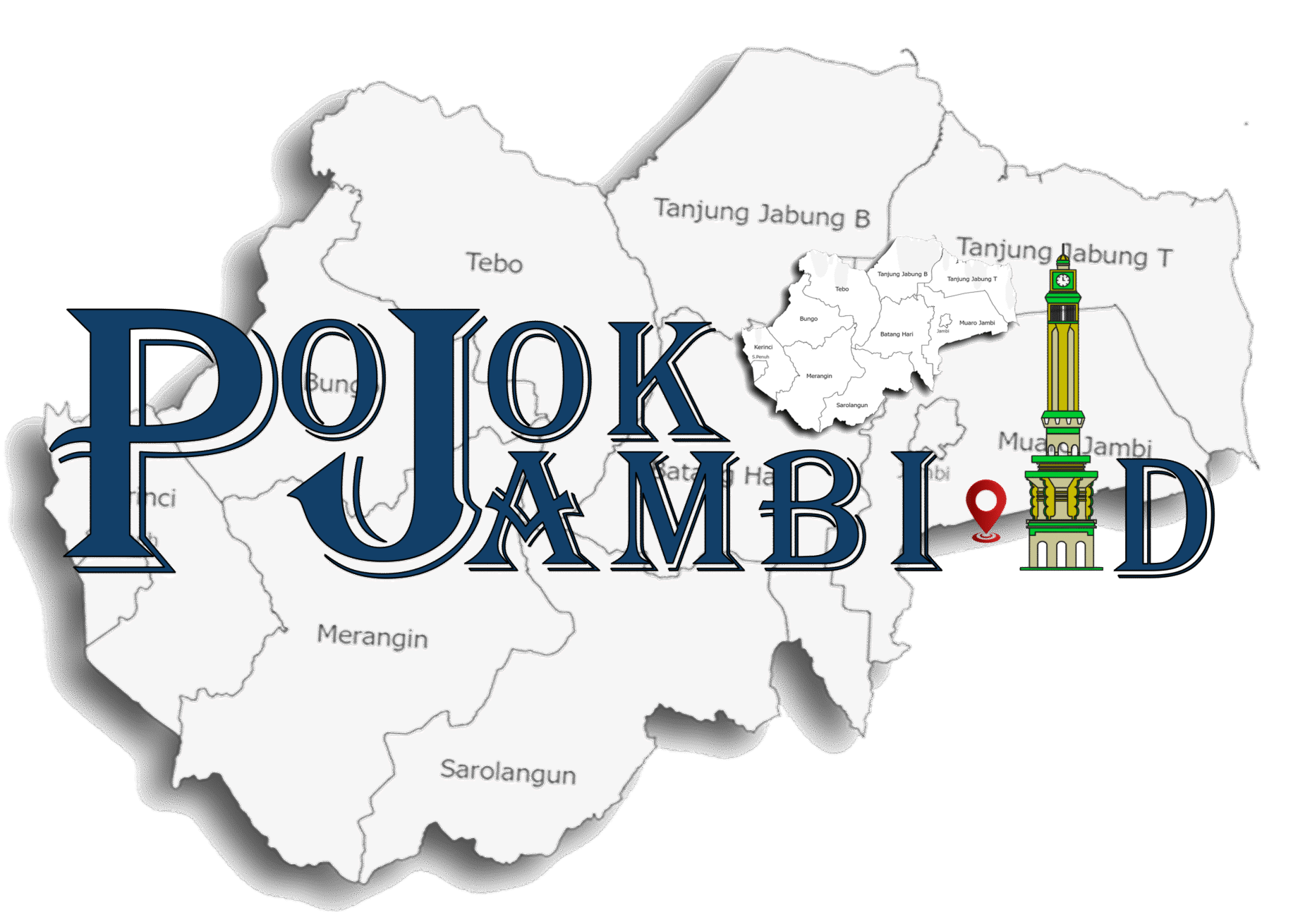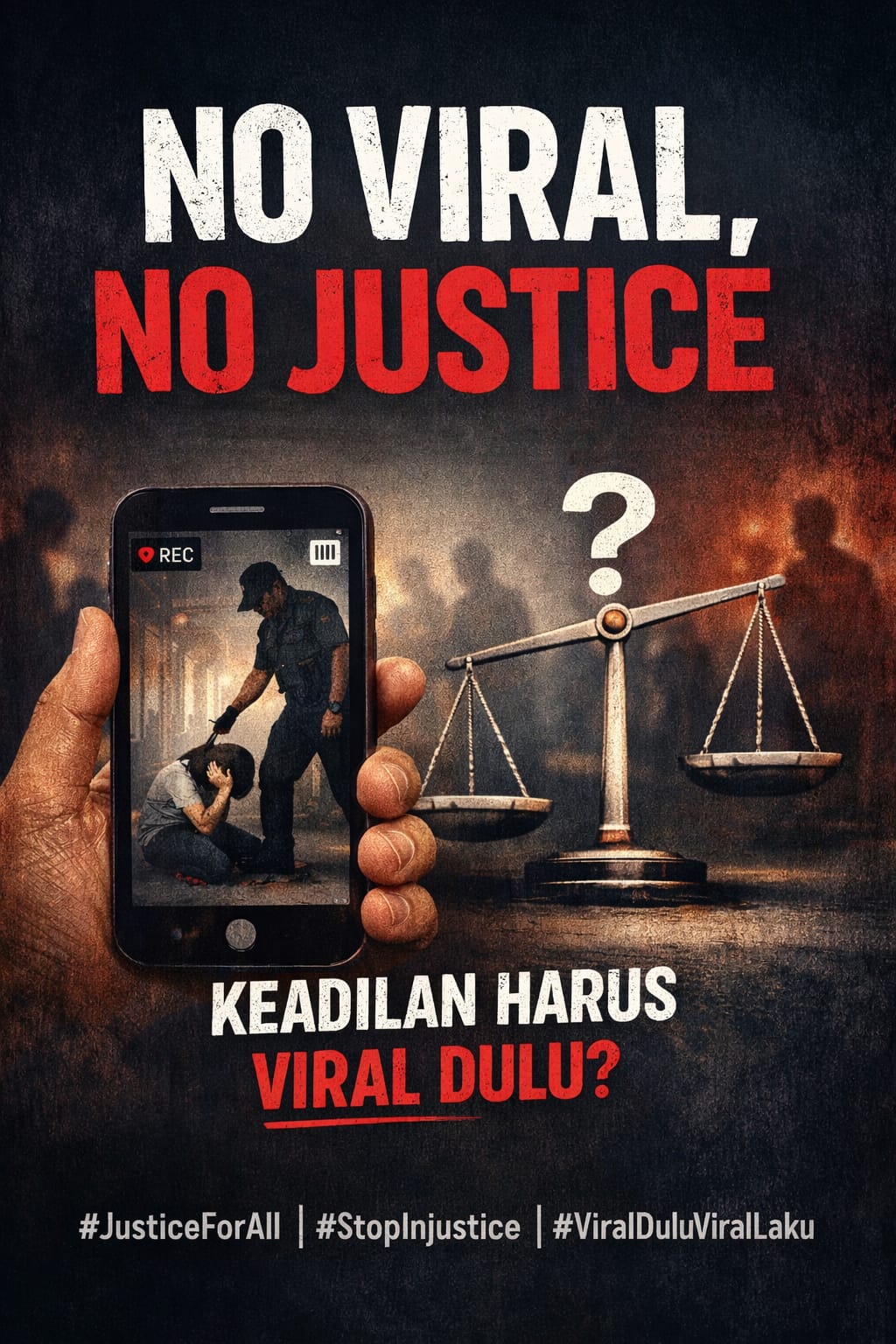Anomali Politik Hukum: Mendesaknya Regulasi Retensi dan Klasifikasi Informasi
Penulis : Yudha Eko Prastito (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi)
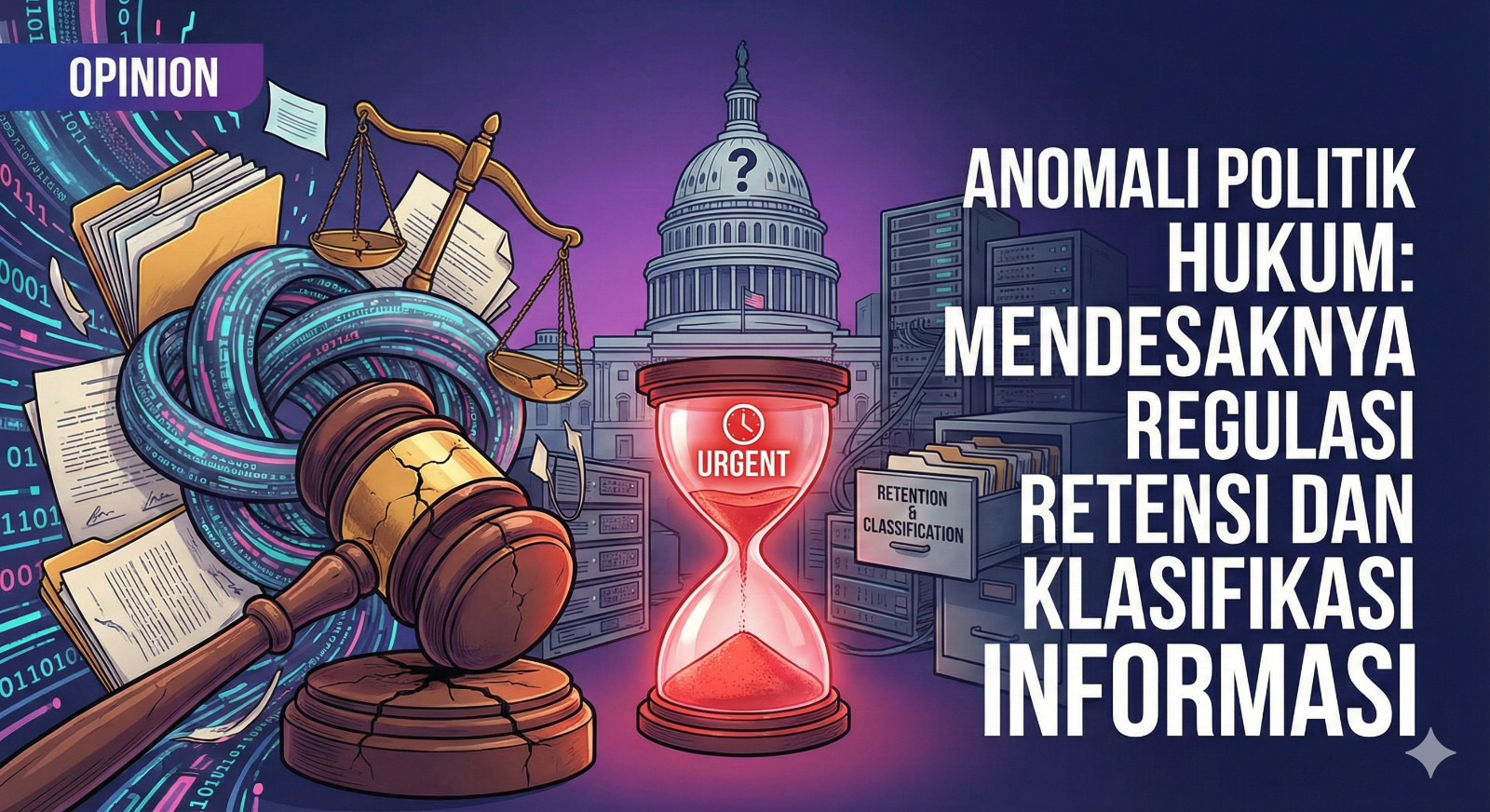
Oleh: Yudha Eko Prastito (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi)
Pojokjambi.id – Dalam perspektif politik hukum, hukum adalah produk dari kehendak politik (political will) penguasa untuk mencapai tujuan negara, yaitu ketertiban dan kepastian. Di era informasi digital saat ini, salah satu aset paling strategis bagi kedaulatan negara bukan lagi hanya wilayah fisik, melainkan data dan informasi. Oleh karena itu, politik hukum nasional seharusnya menempatkan tata kelola informasi (mulai dari penciptaan, penyimpanan (retensi), klasifikasi kerahasiaan, hingga pemusnahan) sebagai agenda prioritas legislasi. Tanpa pengaturan yang jelas, negara membiarkan dirinya berada dalam kekacauan administratif yang berbahaya.
Secara ideal, sebuah negara hukum yang demokratis harus memiliki keseimbangan pengaturan antara transparansi (keterbukaan) dan kerahasiaan (keamanan). Politik hukum harus menarik garis demarkasi yang tegas: informasi apa yang wajib dibuka, informasi apa yang mutlak dirahasiakan (klasifikasi), dan berapa lama informasi tersebut harus disimpan (retensi) sebelum dimusnahkan. Ketiadaan aturan main yang jelas mengenai hal ini menandakan adanya ketidaklengkapan dalam sistem hukum nasional kita.
Namun, realitas hukum (ius constitutum) di Indonesia menunjukkan kondisi yang paradoksal. Kita memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU ITE, UU Kearsipan, dan terakhir UU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Namun, kita belum memiliki satu undang-undang payung atau aturan spesifik yang secara komprehensif mengatur standar “Masa Retensi Informasi Digital” dan “Sistem Klasifikasi Informasi Rahasia” yang berlaku universal bagi lembaga negara maupun korporasi strategis.
Kekosongan hukum spesifik ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Secara deduktif, ketika politik hukum negara absen dalam mengatur standar teknis retensi dan klasifikasi, maka yang terjadi adalah interpretasi liar di lapangan. Setiap instansi atau korporasi membuat aturan main sendiri-sendiri, yang sering kali tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan prinsip keamanan nasional maupun hak asasi manusia.
Dampak pertama dan paling krusial dari ketiadaan UU klasifikasi informasi yang tegas adalah ancaman terhadap keamanan nasional. Tanpa adanya definisi legal yang rigit mengenai apa itu “Rahasia Negara”, “Sangat Rahasia”, atau “Terbatas” yang terintegrasi dengan sistem digital, kebocoran data strategis menjadi sulit ditindak. Penegak hukum kesulitan menjerat pelaku pembocoran data karena kaburnya batas antara informasi publik dan informasi yang dikecualikan (rahasia).
Kedua, dari sisi administrasi pemerintahan, terjadi inefisiensi yang masif. Tanpa aturan masa retensi yang jelas (misalnya: berapa tahun data log akses server harus disimpan, atau berapa lama email kedinasan diarsipkan), lembaga negara cenderung melakukan “penimbunan data” (digital hoarding). Ketakutan akan audit membuat birokrasi menyimpan sampah digital selamanya, yang membebani infrastruktur server negara dan memboroskan anggaran publik.
Ketiga, ketiadaan aturan retensi berdampak pada penegakan hukum pidana, khususnya cybercrime. Penyidik sering kali menemui jalan buntu karena penyedia layanan sistem elektronik (PSE) telah menghapus data jejak digital (log files) yang dibutuhkan sebagai barang bukti, karena tidak ada kewajiban hukum yang memaksa mereka menyimpannya dalam durasi tertentu (data retention mandatory). Politik hukum yang lemah di sini menguntungkan pelaku kejahatan.
Keempat, sebaliknya, ketiadaan batas maksimal masa retensi juga mengancam privasi warga negara. Tanpa aturan pemusnahan yang jelas, data pribadi masyarakat yang pernah dikumpulkan oleh negara atau swasta bisa tersimpan abadi. Ini bertentangan dengan prinsip storage limitation dalam perlindungan data pribadi dan menyandera hak warga negara untuk dilupakan (right to be forgotten).
Kelima, dalam konteks bisnis dan investasi, kekosongan ini menciptakan high cost economy. Pelaku usaha menghadapi keraguan hukum: apakah mereka harus berinvestasi mahal untuk server penyimpanan data selama 10 tahun, atau cukup 5 tahun? Ketidakpastian regulasi retensi ini menjadi risiko kepatuhan (compliance risk) yang membuat investor ragu, karena sewaktu-waktu mereka bisa disalahkan oleh regulator yang berubah-ubah.
Keenam, absennya klasifikasi informasi yang baku memicu sengketa informasi yang berlarut-larut. Komisi Informasi sering kali dibanjiri sengketa karena badan publik secara sepihak melabeli dokumen korupsi atau inefisiensi sebagai “rahasia” tanpa dasar uji konsekuensi yang terstandarisasi oleh undang-undang. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang difasilitasi oleh kekosongan hukum.
Ketujuh, risiko manipulasi sejarah. Arsip dan informasi adalah memori kolektif bangsa. Tanpa politik hukum yang mengatur retensi arsip digital secara ketat, penguasa atau pihak berkepentingan dapat dengan mudah melakukan “pembersihan sejarah” dengan menghapus data-data kebijakan yang kontroversial atau merugikan citra politik mereka di masa depan.
Kedelapan, kerentanan terhadap spionase asing. Di era perang asimetris, informasi yang tidak diklasifikasikan dengan protokol keamanan standar (karena tidak ada UU yang mewajibkannya) adalah santapan empuk bagi intelijen asing. Data strategis kekayaan alam atau pertahanan bisa dicuri tanpa disadari karena dianggap sebagai data biasa yang tidak memiliki label “Rahasia Negara”.
Kesembilan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Arsip Nasional (ANRI), dan Kementerian Kominfo sering kali memiliki pedoman yang berbeda. Tanpa satu UU payung tentang tata kelola informasi strategis, ego sektoral akan terus menghambat integrasi data nasional yang dicanangkan presiden.
Kesepuluh, ketertinggalan dari standar global. Negara-negara maju telah memiliki Official Secrets Act atau regulasi retensi data yang ketat (seperti GDPR di Eropa yang mengatur batasan penyimpanan). Indonesia yang ingin menjadi pemain global ekonomi digital akan sulit bersaing jika infrastruktur hukumnya masih manual dan parsial.
Kesebelas, politik hukum pembentukan undang-undang saat ini tampak lebih fokus pada aspek pragmatis-ekonomis (seperti Omnibus Law Cipta Kerja) dibandingkan aspek tata kelola kedaulatan informasi. Ini menunjukkan adanya disorientasi prioritas legislasi. Padahal, ketahanan informasi adalah fondasi dari ketahanan ekonomi dan politik.
Keduabelas, keraguan legislatif dalam membahas RUU Rahasia Negara di masa lalu (karena takut kembali ke era otoritarian) seharusnya tidak menjadi alasan untuk membiarkan kekosongan hukum. Politik hukum modern harus mampu merumuskan UU Klasifikasi Informasi yang demokratis: melindungi rahasia negara tanpa memberangus kebebasan pers dan kontrol publik.
Ketigabelas, urgensi pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pemerintahan menuntut data yang terstruktur. AI tidak bisa bekerja optimal jika data latihnya (dataset) berantakan—campur aduk antara data sampah (yang seharusnya dimusnahkan) dan data rahasia. Tanpa regulasi retensi dan klasifikasi, adopsi teknologi pemerintah berbasis AI akan gagal.
Keempatbelas, solusi yang dibutuhkan adalah political will dari DPR dan Pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi atau membentuk regulasi baru. Diperlukan undang-undang yang secara spesifik mengatur daur hidup informasi (information lifecycle management) dalam penyelenggaraan negara, yang mengikat secara pidana dan administratif bagi pelanggarnya.
Akhirnya, sebagai konklusi, membiarkan kekosongan hukum terkait masa retensi dan klasifikasi informasi adalah tindakan pembiaran yang membahayakan eksistensi negara hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah pilar stabilitas. Sudah saatnya politik hukum Indonesia bergeser dari sekadar reaktif merespons kasus kebocoran data, menjadi proaktif membangun benteng tata kelola informasi yang kokoh, sistematis, dan berdaulat.